Semua manusia adalah intelektual, namun tidak semua manusia menjalankan fungsi intelektualnya dalam masyarakat. (Antonio Gramsci, 1891-1937)
Mahasiswa baru memasuki dunia kampus dengan motivasi dan orientasi awal yang berbeda, ada yang menganggap kuliah sekadar prestise, ajang cari teman, menambah daya intelektualitas, dan –sebagian besar- sekadar sebagai tempat mendapatkan ijazah agar mudah mendapatkan pekerjaan. Salah satu orientasi mahasiswa adalah intelektualisme yang biasanya baru tersadari dan terbentuk ketika berinteraksi dengan segenap literatur ilmiah yang diramu dengan nalar kritis dan dibenturkan pada realitas. Hal tersebut merupakan penampakan nyata yang menghampiri setiap fenomena kampus hari ini. Pergeseran nilai pun terjadi dalam sebuah kelembagaan pendidikan formal yang menurutku adalah sandaran moralitas bagi masyarakat pada umumnya.
Orientasi yang relatif strategis dalam menjalankan posisi sebagai pioner perubahan di masyarakat ini mulai redup, tergadaikan, dan ditinggalkan. Aktivis mahasiswa banyak yang sekadar jago manajemen organisasi tapi minim kapasitas intelektual, dan sebaliknya banyak “intelektual” yang menahabiskan diri sebagai “intelektual bebas” merasa lebih nyaman bertengger dalam puncak-puncak intelektual yang tak membumi dan elitis. Terkondisikan oleh situasi yang mengikat sisi emosional mahasiswa. Kesadaran palsu muncul sebagai identitas perlawanan, walaupun dikemas dalam bentuk skenario kemanusiaan.
Seharusnya mahasiswa sebagai aktivis dalam arti luas dapat membumi dan memancarkan sisi intelektualitasnya untuk semua, tak hanya berguna untuk komunitasnya saja atau dalam kerangka idealitas tetapi lebih pada kerangka realitas yang ada. Aktivis yang bergerak pada ranah ini sebenarnya lebih mendekati apa yang disebut Antonio Gramsci (1891-1937) sebagai intelektual organik yang mampu mempertautkan teori dan praksis sebagaimana dituju oleh Mazhab Frakfurt agar lebih berguna bagi kehidupan dan memecahkan problem sosial.
George A. Theodorson & Achilles G. Theodorson (1979) mengatakan bahwa kaum intelektual adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinal dan terikat dalam pencarian pemikiran-pemikiran kreatif. Dengan demikian terdapat karakteristik kaum intelektual, yaitu pada penggunaan intelek dan akal pikiran, bukan untuk hal-hal yang bersifat praktis, tapi lebih berorientasi pada pengembangan ide-ide (Azyumardi Azra, 2003). Hal itu memperkuat tesis bahwa kaum intelektual pada dasarnya bersifat progresif revolusioner, meskipun lebih diwujudkan dalam revolusi pemikiran bukan revolusi fisik. Hal inilah yang menjadikan intelektual sebagai berperilaku, bersikap, dan berkarakter kritis. Dan sebagai kritikus, kaum intelektual menyatakan pikiran dan kritiknya secara jelas dan bijak.
Sejatinya insan intelektual dengan beberapa kualifikasi seperti di atas bukanlah monopoli pendidikan formal, terutama perguruan tinggi. Bahkan banyak kaum intelektual lahir dari luar benteng menara gading kampus. Mereka mampu mengembangkan pemikiran sendiri hingga mencapai kemampuan pemikiran dan perilaku intelektual. Dengan adanya kerangka analisis kritis, mahasiswa pun wajib memiliki sebuah visi dan misi tentang agenda gerakan sosial. Hingga menjadi sebuah stimulan dalam evaluasi gerakan nilai.
Sebaliknya banyak jebolan perguruan tinggi yang lebih tepat digolongkan sebagai intelegensia daripada intelektual. Intelegensia menurut Gouldner (1979) adalah mereka yang minat intelektualnya secara fundamental bersifat teknis. Hal ini karena sebagai produk perguruan tinggi mereka telah menerima pendidikan yang membuat mereka mampu memegang pekerjaan sesuai dengan bidang dan profesi ilmunya (Bottomore, 1964).
Donald Wilhelm (1979) menambahkan, bahwa banyak tamatan perguruan tinggi mengalami kemandegan atau kehilangan kapasitas intelektualnya ketika mereka masuk ke dalam birokrasi dan rutinitas akademis di perguruan tinggi atau di manapun mereka bekerja. Perguruan tinggi yang diharapkan dapat berperan sebagai avant garde, inovator dan pembaharu masyarakat kemudian terjebak dalam mekanisme birokrasi dan spesialisasi atau profesinya di mana mereka terus menerus mengolah dan menghasilkan informasi serta pikiran dalam bidang mereka masing-masing yang relatif sempit.
Hal itu tentu bertentangan dengan kenyataan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat sekarang tak dapat dipecahkan dengan pendekatan sempit semacam itu; pemecahan masalah sekarang membutuhkan pendekatan menyeluruh, interdisipliner dan berwawasan luas.
Perubahan yang terjadi terhadap sisi katakteristik merupakan langkah untuk menjawab kembali tantangan dari yang namanya entitas gerakan intelektual. Mahasiswa dalam hal ini harus lebih memahami secara parsial dan integral sehingga konsep sebuah gerakan terlihat secara holistik. Dari berbagai aspek kemasyarakatan inilah rumusan dari bentuk formulasi gerakan intelektual, mencoba berdiri di atas realitas kebenaran.
Pertanyaan menggelitik yang layak diajukan adalah, apakah kita termasuk intelektual atau sekadar intelegensia? Kita mahasiswa biasa atau luar biasa? Atau dalam perenungan yang lebih dalam lagi, “Selama hidup kita di kampus ini, kita akan menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan tersebut dengan karya apa?” Kita ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Dan semuanya kembali pada diri kita sendiri untuk menjawab itu semua. Wallahu a’lam bishsawab. *Sebuah renungan bersama buat kawan-kawan
Oleh Irmal Dhal
(Mahasiswa Perikanan Unhas Angkatan 2003)
Seharusnya mahasiswa sebagai aktivis dalam arti luas dapat membumi dan memancarkan sisi intelektualitasnya untuk semua, tak hanya berguna untuk komunitasnya saja atau dalam kerangka idealitas tetapi lebih pada kerangka realitas yang ada. Aktivis yang bergerak pada ranah ini sebenarnya lebih mendekati apa yang disebut Antonio Gramsci (1891-1937) sebagai intelektual organik yang mampu mempertautkan teori dan praksis sebagaimana dituju oleh Mazhab Frakfurt agar lebih berguna bagi kehidupan dan memecahkan problem sosial.
George A. Theodorson & Achilles G. Theodorson (1979) mengatakan bahwa kaum intelektual adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinal dan terikat dalam pencarian pemikiran-pemikiran kreatif. Dengan demikian terdapat karakteristik kaum intelektual, yaitu pada penggunaan intelek dan akal pikiran, bukan untuk hal-hal yang bersifat praktis, tapi lebih berorientasi pada pengembangan ide-ide (Azyumardi Azra, 2003). Hal itu memperkuat tesis bahwa kaum intelektual pada dasarnya bersifat progresif revolusioner, meskipun lebih diwujudkan dalam revolusi pemikiran bukan revolusi fisik. Hal inilah yang menjadikan intelektual sebagai berperilaku, bersikap, dan berkarakter kritis. Dan sebagai kritikus, kaum intelektual menyatakan pikiran dan kritiknya secara jelas dan bijak.
Sejatinya insan intelektual dengan beberapa kualifikasi seperti di atas bukanlah monopoli pendidikan formal, terutama perguruan tinggi. Bahkan banyak kaum intelektual lahir dari luar benteng menara gading kampus. Mereka mampu mengembangkan pemikiran sendiri hingga mencapai kemampuan pemikiran dan perilaku intelektual. Dengan adanya kerangka analisis kritis, mahasiswa pun wajib memiliki sebuah visi dan misi tentang agenda gerakan sosial. Hingga menjadi sebuah stimulan dalam evaluasi gerakan nilai.
Sebaliknya banyak jebolan perguruan tinggi yang lebih tepat digolongkan sebagai intelegensia daripada intelektual. Intelegensia menurut Gouldner (1979) adalah mereka yang minat intelektualnya secara fundamental bersifat teknis. Hal ini karena sebagai produk perguruan tinggi mereka telah menerima pendidikan yang membuat mereka mampu memegang pekerjaan sesuai dengan bidang dan profesi ilmunya (Bottomore, 1964).
Donald Wilhelm (1979) menambahkan, bahwa banyak tamatan perguruan tinggi mengalami kemandegan atau kehilangan kapasitas intelektualnya ketika mereka masuk ke dalam birokrasi dan rutinitas akademis di perguruan tinggi atau di manapun mereka bekerja. Perguruan tinggi yang diharapkan dapat berperan sebagai avant garde, inovator dan pembaharu masyarakat kemudian terjebak dalam mekanisme birokrasi dan spesialisasi atau profesinya di mana mereka terus menerus mengolah dan menghasilkan informasi serta pikiran dalam bidang mereka masing-masing yang relatif sempit.
Hal itu tentu bertentangan dengan kenyataan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat sekarang tak dapat dipecahkan dengan pendekatan sempit semacam itu; pemecahan masalah sekarang membutuhkan pendekatan menyeluruh, interdisipliner dan berwawasan luas.
Perubahan yang terjadi terhadap sisi katakteristik merupakan langkah untuk menjawab kembali tantangan dari yang namanya entitas gerakan intelektual. Mahasiswa dalam hal ini harus lebih memahami secara parsial dan integral sehingga konsep sebuah gerakan terlihat secara holistik. Dari berbagai aspek kemasyarakatan inilah rumusan dari bentuk formulasi gerakan intelektual, mencoba berdiri di atas realitas kebenaran.
Pertanyaan menggelitik yang layak diajukan adalah, apakah kita termasuk intelektual atau sekadar intelegensia? Kita mahasiswa biasa atau luar biasa? Atau dalam perenungan yang lebih dalam lagi, “Selama hidup kita di kampus ini, kita akan menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan tersebut dengan karya apa?” Kita ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Dan semuanya kembali pada diri kita sendiri untuk menjawab itu semua. Wallahu a’lam bishsawab. *Sebuah renungan bersama buat kawan-kawan
Oleh Irmal Dhal
(Mahasiswa Perikanan Unhas Angkatan 2003)
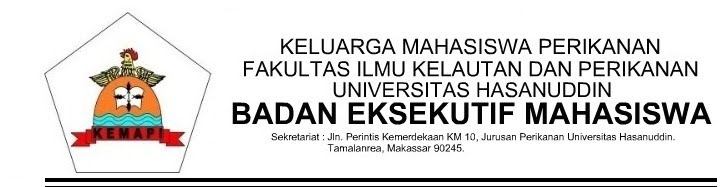

Tidak ada komentar:
Posting Komentar